Sandilara dan Bagaimana Manifestasi Hari Rayanya: Catatan Atas “Ana sing Ra Ana” — Teater Sandilara
[Erhan Al Farizi]. Persoalan hari raya dalam seluruh agama dan kepercayaan tentunya mengusung makna kontemplatif. Hari raya bukanlah perayaan kegagahan untuk melepaskan tanggung jawab sebagai manusia.
Agama Islam misalnya mengusung esensi Idul Fitri dalam wujud saling memaafkan sebab betapa manusia adalah lumbung salah dan dosa. Agama Kristen misalnya merayakan Natal untuk memperingati Yesus Kristus yang lahir lewat kasih sayang Allah untuk umat-Nya, manusia yang lahir dari cinta maka sudah sepantasnya menyebarkan cinta itu kepada sesamanya. Ya, bagaimanapun hari raya adalah momen untuk menggali kedalaman jiwa kemanusiaan.
Hal tersebutlah yang tampak dalam perayaan menuju hari lahir sepuluh tahunnya Teater Sandilara. Teater Sandilara memang lahir atas dasar untuk tidak meninggalkan masyarakatnya. Maka Sandilara merencanakan pementasan di sepuluh titik untuk merayakan sepuluh tahun keberjalanan mereka.
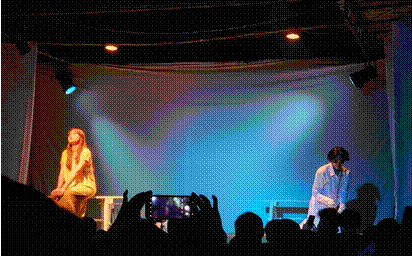
Titik awal dari pementasan ini mereka helat di Perumahan Berlian Permai di Sukoharjo pada tanggal 15 Agustus 2023 lalu. Suasana menjelang perayaan hari kemerdekaan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat Perumahan Berlian Permai dan Teater Sandilara.
Di tahun yang ke sepuluh ini, Sandilara kembali merenungi kebermulaan mereka. Mereka ingin kembali fitri dengan cara menyambangi kembali penonton-penonton mereka.
Sandilara sadar bahwa aspek pertunjukan tidak akan berhasil tanpa kehadiran panggung, penampil, dan terutama penonton. Sepuluh tahun Sandilara tentu tidak dapat dilepaskan dari aspek kedatangan dan kepergian bagian-bagian mereka.
Kedatangan dan kepergian tersebut dapat berupa aspek gagasan, elementer pertunjukan, maupun hal mendasar yang jarang masuk dalam diskusi teater: keanggotaan. Kedatangan dan kepergian tersebut kemudian memantik proses Sandiwara Ana sing Ra Ana. Naskah ini secara mendasar menceritakan tentang kehadiran dan ketidakhadiran manusia bagi manusia lain. Barangkali naskah ini dipersembahkan kepada mereka yang masih ada maupun yang sudah meninggalkan kelompok ini, barangkali.
Hantu dan Kehilangan Orang Terdekat
Sandiwara Ana sing Ra Ana mengisahkan tentang Nonot yang menjadi hantu karena tidak tenang dengan kematiannya. Kabar yang tersiar adalah Nonot mati karena tabrak lari yang tak disengaja. Nonot hendak meluruskan kabar tersebut karena realita yang telah terjadi tidaklah seperti itu. Kepergiaan Nonot tentu membuat orang terdekat merasa begitu kehilangan. Orang terdekat tersebut adalah Marni yang merupakan kekasih Nonot. Setelah setahun kepergian Nonot, Marni masih belum sembuh dari perasaan kehilangan itu.
Sandiwara diawali dengan pembukaan oleh sutradara sekaligus penulis naskah Sandiwara Ana sing Ra Ana, Idham Ardi Nurcahyo. Idham membuka hari raya Teater Sandilara itu dengan retrospeksi kelompok itu yang pada awalnya menjemput penonton mereka dari satu desa ke desa lain.
Idham juga menegaskan bahwa proses ini berangkat dari perasaan kehilangannya, terutama kehilangan ibu beberapa tahun lalu. Ketika membicarakan tentang ketidakutuhan, sontak muncullah tokoh hantu yang bernama Nonot itu.
Simbol ketidakutuhan seseorang itu dikonkretisasikan oleh sutradara lewat wujud hantu. Sebuah simbol yang menarik menurut saya, ketidakutuhan adalah hal yang menakutkan bagi manusia. Ketidakutuhan seringkali menghantui manusia dalam keadaan siap ataupun tidak siap.
Tapi bagaimana pun, manusia tidak dapat hidup dengan rasa takut. Justru akan berbahaya jika manusia tidak menyisakan sama sekali perasaan takut di benaknya. Ketakutan adalah sifat alami manusia, ketakutan adalah perasaan paling purba yang dimiliki manusia.
Pementasan pun dimulai dengan perkenalan oleh Nonot. Ia tidak dapat mati dengan tenang karena hoaks tentang kematiannya yang sudah terlanjur dipercaya masyarakat. Kemudian masuklah Marni yang dihantui oleh rasa sakit atas kehilangan kekasihnya. Kehilangan yang mendalam tersebut kemudian membuat murka bapak Marni, Sarno. Sarno menduga bahwa Marni telah dibuat gila oleh perasaan sedih itu. Watak Sarno yang keras akhirnya ditengahi oleh Juwariyah, istrinya, yang masih memiliki ketebalan kasih sayang kepada anaknya. Dalam kecamuk tersebut, Nonot tetap berusaha berkomunikasi dengan Marni untuk meluruskan beberapa hal walaupun hasilnya nihil.
Kendatipun mengangkat isu terkait tragedi, nyatanya pertunjukan ini dibawa dengan suasana komedi. Pementasan ini tidak tergesa mencekoki penonton untuk mendidik dirinya. Pementasan ini memberi keleluasaan penonton untuk memilih fungsi sastra dulce et utile (mendidik dan menghibur). Penonton diizinkan memilih kedua kebermanfaatan tersebut dan tetap dipersilakan jika hanya ingin mengambil salah satu kebermanfaatan tersebut.
Hiburan penonton bertambah ketika hadirnya Lukito yang merupakan orang gila. Berbagai teriakan, tertawaan, dan kecrohan dari penonton direspons dengan porsi pas oleh sang aktor.
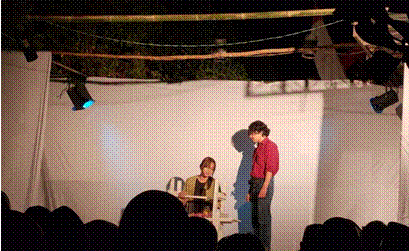
Walaupun memiliki ketakutuhan dalam kewarasan akalnya, tetapi tokoh Lukito memiliki kelebihan untuk dapat melihat kematian Nonot. Logika penonton kembali dipermainkan melalui Lukito. Sejatinya pengocokan logika sudah terjadi sejak awal ketika penjudulan pentas ini, Ana Sing Ra Ana merupakan frasa paradoks yang juga dirancang untuk mengocok logika oleh penulis sekaligus sutradara.
Lukito merasa iba karena ternyata Nonot tidak sekadar mati, tapi ternyata dibunuh. Lukito akhirnya menjadi penyambung lidah arwah Nonot untuk meluruskan berita kematiannya. Dapat ditebak bahwa Lukito akhirnya hanya dianggap mengganggu ketenteraman keluarga Sarno. Sarno akhirnya menunjukkan ketidakberdayaan hatinya, bahwa dia hanya ingin Marni merelakan kepergian Nonot.
Dalam suasana yang gamang, terjadilah perubahan pola artistik. Artistik panggung yang semula hanya berbentuk kursi kemudian diakrobatikkan menjadi bentuk makam. Kursi yang awalnya menjadi simbol kehadiran, akhirnya diputar menjadi makam yang menjadi simbol kepergian.
Artistik dan panggung yang dirancang sederhana tersebut ternyata bisa memberi pemaknaan yang tidak ala kadarnya. Kemudian muncul tokoh Bayu yang mengakui dosa di kuburan Nonot. Kemudian Marni pun turut menziarahi kuburan Nonot, dan memulai perbincangan pertama dengan Bayu. Kelanjutan cerita ini sesuai dengan yang diteriakkan penonton, bahwa Bayu kemudian jatuh cinta kepada Marni. Sekali lagi, Bayu menari di atas penderitaan Nonot tanpa sepengetahuan Marni.
Menonton pentas ini, awalnya saya tidak menjumpai isu sosial yang biasanya getol dilantangkan Teater Sandilara. Sandiwara Ana sing Ra Ana justru didominasi oleh isu personal tentang kehilangan. Dugaan tersebut kemudian meluntur ketika diceritakannya Bayu yang merupakan pesuruh dari perusahaan air minum yang mengeksploitasi desa.
Tensi pertunjukan memuncak ketika Lukito sebagai saksi Nonot kemudian melantangkan tuduhannya. Lukito kemudian memberi kabar kepada keluarga Sarno bahwa Bayulah aktor dibalik pembunuhan Nonot. Lukito kembali mengocok logika penonton dengan memberitahu bahwa bukti tersebut tidak perlu ditelusuri secara hukum, tetapi cukup dengan hati nurani. “Buktine ono ing kene,” tukas Lukito seraya mengarahkan telunjuk kepada organ tubuh hati Bayu berada.
Alur dalam pementasan tersebut ditutup dengan pertemuan Marni dengan Nonot. Sepasang kekasih tersebut akhirnya dapat berbincang untuk terakhir kalinya. Kemudian, kembali lagi, Marni harus merasakan ke-“ada”-an Nonot dalam ketidak-“ada”-annya.
Hari Raya dan Munajat Pendewasaan
Kisah tentang Markesot karya Cak Nun atau Cak Dlahom dari Rusdi Mathari mengajak kita untuk mendalami hari raya. Markesot dengan tingkah eksentriknya mampu menggugah humanisme manusia.
Begitupun Cak Dlahom yang lebih memilih menolong tetangganya yang yatim piatu dibanding menghabiskan waktu dan hidangan bersama keluarga. Dua kisah tersebut dapat menyadarkan kita bahwa perayaan bukanlah perkara mengeksklusifkan diri. Sikap tersebut adalah kearifan yang melampaui perayaan secara harfiah.
Dua tokoh fiktif itu menunjukkan bahwa hari raya bukanlah sekadar momen untuk berpesta dan mengagungkan diri sendiri. Kebahagiaan yang lebih utuh nyatanya justru datang dari momen berbagi.
Kebahagiaan yang diimplementasikan dengan berbagi inilah yang coba ditawarkan Teater Sandilara dalam perayaan satu dekadenya. Tentunya untuk menunjang proses ini, Teater Sandilara terlebih dahulu mengalami penikmatan dalam internal mereka. Kemudian kenikmatan dan kebahagiaan ini mereka bagi kepada penonton.
Melalui rasa ingin berbagi, diharapkan setiap insan dapat saling melengkapi kebahagiaan antar manusia. Hal tersebut tercermin dalam obrolan yang terjadi setelah pementasan berlangsung. Dalam obrolan tersebut masyarakat cukup mengapresiasi kehadiran Sandilara. Bahkan muncul gagasan untuk membuat sanggar teater di Perumahan Berlian Permai. Semoga gagasan tersebut tidak berhenti sebagai gagasan.
Setiap umat tentu mengharapkan pertumbuhan dan perkembangan ketika merayakan hari raya. Harapan tersebut muncul dengan kesadaran untuk meninggalkan hal-hal buruk, dan semakin mendekati hal-hal baik. Hari raya adalah momen untuk bermuhasabah mendewasakan diri. Mendewasakan diri bukan berarti harus meninggalkan ketulusan kekanak-kanakan, tetapi lebih ke arah yang semakin menjauhi ketermanjaan-ketermanjaan.
Konsep pendewasaan ini juga terlihat dalam artistik yang dirancang oleh Sandilara. Sangat kentara bahwa Sandilara mengadopsi konsep “gagah dengan kemiskinan” dari W.S. Rendra. Gagasan ini adalah kelapangan dada terhadap fasilitas desa yang jauh dari kemegahan estetika seperti di kota. Konsep ini berkesesuaian dengan pentas keliling karena kesiapan merespons tempat memang harus diperhitungkan secara efektif dan efisien.
Teater Sandilara juga membuktikan bahwa kedewasaan bukan sekadar seberapa jauh potensi untuk menghasilkan, tetapi seberapa bijak menyikapi perasaan ditinggalkan. Sedari anak-anak, tentu sudah banyak hari raya yang kita lewati dan selalu berubah-ubah perasaan itu. Kakek yang sepuluh tahun lalu telah tiada, Nenek yang tiga tahun lalu telah tiada, atau bahkan orang tua kandung yang tahun lalu telah tiada. Perasaan setiap hari raya memang tidak pernah sama. Tetapi saling berbagi dan tetap mengusahakan sebaik-baik hari esok bukankah pula sebaik-baik pilihan? Selamat merayakan hari apa pun.
